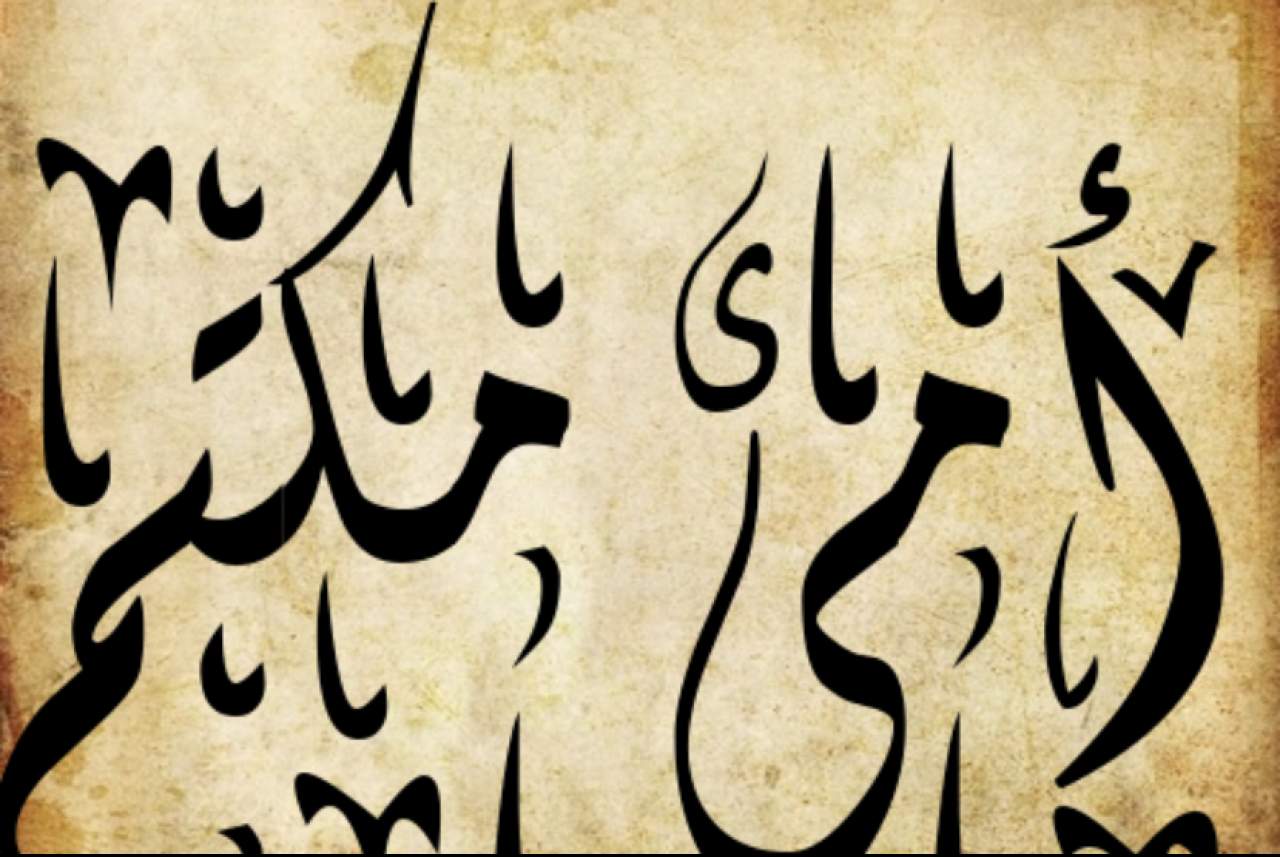Refleksi
Paradoks Dunia Antroposen
Manusia di dunia antroposen adalah titik sentral dari relasi alam dan lingkungannya.
Oleh PROF HAEDAR NASHIR
OLEH PROF HAEDAR NASHIR
Amerika Serikat ribut mengecam Indonesia soal aplikasi PeduliLindungi Covid-19 yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia menjawab kritik. Negara lain juga memiliki aplikasi serupa, seperti Singapura (TraceTogether), Cina (The Alipay Health Code), India (Aarogya Setu), dan Australia (COVIDSafe).
Baiklah, perlu saksama agar aplikasi PeduliLindungi tidak disalahgunakan yang berpotensi mengorbankan hak privasi warga Indonesia. Tapi, aneh sekali sikap suatu negara soal hak asasi manusia.
Negara-negara itu bungkam seribu bahasa ketika pada pekan yang sama, Israel dengan ganas menyerang kaum Muslimin di Masjidil Aqsha. Para pemegang lisensi kritis atas pelanggaran HAM di berbagai negara itu bersatu bisu.
Padahal, serangan polisi Israel pada bulan suci Ramadhan itu melukai lebih 152 warga sipil, menambah daftar panjang kekejaman dan invasi Israel terhadap bangsa Palestina.
Betapa berat derita rakyat Palestina sejak tahun 1948 tiada akhir. Selain kehilangan tanah air yang sah, mereka terus-menerus diteror, diserang, ditembaki, dan diagresi secara fisik sepanjang hidupnya. Perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban.
Sungguh ironi. Pada era dunia modern abad ke-21, negara-negara maju yang mewakili peradaban dunia modern yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan justru bisu atas pelanggaran demi pelanggaran HAM oleh Israel.
Pelanggaran hak individu dan kasus-kasus lokal di Dunia Ketiga selalu menjadi sorotan keras, tapi pelanggaran berat berulang kali yang mengorbankan banyak nyawa manusia dan kemerdekaannya didiamkan. Dunia lumpuh matahatinya oleh hanya satu negara. Inilah paradoks peradaban pada era dunia antroposen!
Dunia lumpuh mata hatinya oleh hanya satu negara. Inilah paradoks peradaban pada era dunia antroposen!
Era antroposen
Antroposen (anthropocene) adalah kala yang bermula ketika aktivitas manusia memiliki pengaruh global terhadap ekosistem bumi dan semesta raya. Sepanjang sejarah peradaban, manusia selalu berpengaruh terhadap alam lingkungannya.
Pada era mistis, menurut Van Perseun, manusia menyatu dengan alam. Lalu pada masa ontologis berjarak dengan alam. Pada era fungsional, manusia mengeksploitasi alam. Pada fase fungsional dan saintifik itulah dunia antroposen terbentuk kuat yang memberi pengaruh fundamental dan masif terhadap alam.
Para ilmuwan, khususnya ahli geologi seperti Paul Crutzen (2002) dan Steffen dan kawan-kawan (2004), masih berdebat mengenai sejak kapan era antroposen bermula. Apakah sejak revolusi pertanian dan awal revolusi industri yang masih berada dalam mata rantai era holosen?
Kuat kecenderungan era baru itu secara signifikan dimulai setelah Perang Dunia Kedua ketika bom atom pertama dijatuhkan di Alamogordo, New Mexico, tahun 1945, kemudian di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, dalam Perang Dunia Kedua pada tahun yang sama, yang secara fundamental telah mempermak wajah dan ekosistem bumi akibat ulah manusia-manusia serakah yang merasa digdaya di era modern.
Pertalian epos antroposen dengan alam pikiran antroposentrisme pada era modern pascarevolusi industri kesatu (mesin uap), kedua (listrik), ketiga (komputer), dan keempat (teknologi informasi) sangatlah erat. Antroposentris menempatkan manusia sebagai jangkar segala aktivitas dan orientasi hidup, titik balik ekstrem dari relasi teosentris.
Lahirlah kredo baru humanisme, hak asasi manusia, demokrasi, ilmu pengetahuan, dan modernitas di atas takhta antroposentrisme yang menyertai gerakan renaisans dan aufklarung di Eropa dan terus menyebar ke seluruh dunia modern.
Pertalian epos antroposen dengan alam pikiran antroposentrisme pada era modern pascarevolusi industri kesatu (mesin uap), kedua (listrik), ketiga (komputer), dan keempat (teknologi informasi) sangatlah erat.
Orientasi hidup bangsa-bangsa pada era antroposen dengan nalar antroposentrisme semestinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara autentik. Namun, karena ambisi berlebih untuk membangun imperium ala kejayaan Romawi Agung pada era modern, sebagaimana digelorakan oleh Niccolo Machiavelli tentang etos politik “virtuoso”, maka yang menguat ialah nafsu ekspansi dan hegemoni manusia.
Mangsanya tiada lain sesama manusia dan bangsa-bangsa lain yang dianggap terbelakang dan harus dimodernkan. Lahirlah episode tragis kolonialisme yang meluas pasca era humanisme-modernisme yang menciptakan tragedi terbesar dunia di hampir seluruh jazirah Asia, Afrika, dan Amerika Latin nan nestapa.
Dunia antroposen dengan nalar humanisme dunia modern dan antroposentrisme yang ambigu akhirnya melahirkan paradoks dunia kemanusiaan. Manusia menjadi hilang kemanusiaannya yang autentik dan meluap hasrat penaklukannya untuk menguasai manusia lain tanpa pijakan akal budi. Insan modern juga ganas merusak alam dan ekosistem tempat mereka hidup.
Meminjam istilah Noah Harari, umat manusia berubah wataknya dari homo sapiens ke homo deus karena kuasa iptek yang supercanggih. Manusia tingkat dewa itu akhirnya menjelma menjadi sang penakluk dan penghancur peradaban dirinya.
Padahal, keangkuhan manusia antroposen itu sudah lama digugat oleh para pemikir dan pegiat kemanusiaan, sebagaimana satire sebuah film dokumenter tahun 2012 karya Samuel McAnallen, The Superior Human?
Manusia antroposen yang serbadigdaya dan menjadi makhluk dewa itu sungguh bebal karena telah kehilangan jangkar metafisika kehidupan seperti dikritisi Roy Scranten dalam Learning How to Die in the Anthropocene (2014). Director of Environmental Humanities Initiative tersebut memperingatkan, “Tantangan terbesar yang dihadapi manusia abad ini adalah tantangan filosofis, yakni bagaimana mengerti bahwa peradaban ini di ambang kematian.”
Penulis Modern Ethics in 77 Arguments tahun 2017 itu menegaskan bahwa kematian dunia kemanusiaan dapat beragam wajah yang bersifat alami, budaya, ekonomi, dan lainnya yang meniscayakan lahirnya kearifan baru dalam menghadapi kehidupan manusia dengan segala ekosistemnya yang kompleks.
Dunia antroposen dengan nalar humanisme dunia modern dan antroposentrisme yang ambigu akhirnya melahirkan paradoks dunia kemanusiaan.
Kearifan baru dunia antroposen tak pernah hadir karena ambisi kuasa dan virus dendam “deprivasi relatif” manusia-manusia tipe sang penakluk. Bangsa yang pernah mengalami tragedi Auschwitz di tiga kamp konsentrasi yang mengerikan dalam sejarah hitam Holocaust tahun 1945 semestinya merasakan betapa hancur kehidupan akibat kekejaman politik Nazi Jerman kala itu agar tidak mengulangi nista yang sama pada era peradaban modern.
Kenyataannya, hukum homo homini lupus terus berlangsung di atas takhta megah kredo hak asasi manusia (HAM) universal yang kehilangan makna autentik. Deklarasi demi deklarasi PBB pun hanya serpihan hiasan kertas belaka.
Politik HAM berstandar ganda menjadi pemandangan lumrah tatanan global saat ini. Para tokoh dunia dan pegiat HAM terperangkap sangkar-besi kepentingan-kepentingan serpihan. Elite-elite agama, cendekiawan, dan kaum nasionalis bersuara nyaring penentang radikalisme-terorisme pun mengidap kebisuan yang sama. Itulah dramaturgi dunia antroposen saat ini!
Merusak alam
Manusia di dunia antroposen adalah titik sentral dari relasi alam dan lingkungannya. Manusia dengan kekuatan akal pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi hasil kreasinya yang canggih makin perkasa dalam mengolah, mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan menaklukkan alam.
Pengaruh manusia digdaya itu makin dominan dan sewenang-wenang. Bukan hanya membangun, untuk menghancurkan bumi dan planet raya pun manusia modern seolah memiliki keabsahan untuk melakukannya tanpa rasa iba.
Alam seolah menjadi budak dan objek penderita yang boleh diperlakukan sekehendaknya. Sosok-sosok perkasa yang memorak-porandakan tatanan berbangsa dan sistem hidup bersama malah menjadi “idola”, apalagi bila bersembunyi di balik takhta istana.
Di ranah ekologi lahir tragedi baru “the climate change”. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) dengan tegas menyuarakan ancaman besar perubahan iklim yang dahsyat. Bumi makin panas dan ekosistem rusak disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu tertentu.
Terjadi peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca itu menurut para ahli disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia, seperti emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah, dan kegiatan-kegiatan industri yang berlangsung masif. Alam dan isinya dikuras habis-habisan secara tak bertanggung jawab, seperti kata pepatah, “habis manis sepah dibuang”.
Manusia di dunia antroposen adalah titik sentral dari relasi alam dan lingkungannya.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang berlangsung masif itu sistem kehidupan dunia menghadapi apa yang disebut David Wallace-Wells (2019) sebagai “The Uninhabitable Earth”, yakni kisah tentang masa depan kehidupan, ketika bumi tidak dapat lagi dihuni. Ancaman perubahan iklim lebih total dan lebih luas ketimbang tragedi bom nuklir.
Berbagai bencana alam yang tidak lagi alami, badai, kelaparan, laut yang sekarat, udara yang tidak dapat dihirup, wabah akibat pemanasan, ambruknya ekonomi, konflik akibat iklim, semua terkait dengan perubahan iklim global. Kehidupan di ambang kepunahan menyerupai kiamat, the day after.
Manusia tidak dapat lagi memilih planet karena inilah tempat satu-satunya di alam semesta yang disebut sebagai home atau rumah tinggal. Elisabeth Kohler (2014) bahkan mengungkap fakta “The Sixth Extinction”, tentang kepunahan dahsyat episode keenam dari ratusan jenis hewan dan spesies yang hilang, penanda kehancuran habitat alam dalam satu abad terakhir.
Paradoks dunia antroposen yang terkait ekosistem bumi bersumber dari kerakusan manusia dalam mengeksploitasi alam yang melampaui batas. Meski para pebisnis raksasa, industrialis, inovator, dan CEO bergelimang uang seperti Elon Musk dan kawan-kawan berambisi membuka kehidupan baru di planet Mars.
Hasil akhirnya akan bernasib sama. Bintang Siarah Mars akan nestapa seperti Bumi yang hancur akibat keserakahan manusia di era post-antroposen. Kota-kota megapolis supermodern di setiap negara, yang dibangun di kawasan baru, akhirnya menjadi lapuk dan rusak kembali seperti nasib buruk kota-kota modern sebelumnya karena salah kaprah dan rancang-bangun serakah. Hutan dan ekosistem hancur di atas kemegahan “green city” dan “forest city” yang absurd sarat keangkuhan legasi.
Hasrat-hasrat ambisius membangun kemegahan kota, industri, dan segala proyek raksasa di atas kerusakan lingkungan adalah awal kehancuran alam tempat habitat manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk Tuhan lainnya hidup yang tercerabut. Fakta membangun yang menghancurkan itulah yang telah lama diperingatkan para ilmuwan, seperti Björn Hettne tentang “ironi pembangunan” khususnya di Dunia Ketiga (1984).
Inilah paradoks pembangunan yang merusak alam dan kehidupan sebagaimana diperingatkan Tuhan dalam Alquran (QS al-Baqarah [2]: 11): “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.” Legasi membangun, tapi merusak!
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Lelaki Buta yang Mencintai Rasulullah SAW
Meski tidak dianugerahi penglihatan, Ibnu Ummi Maktum mendapat keistimewaan berupa kecintaan terhadap agama meski nyawa taruhannya.
SELENGKAPNYAPelabuhan Merak Makin Padat
Sebanyak 1,15 juta kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabotabek.
SELENGKAPNYAIdul Fitri dan Mudik Spiritual
Kesalehan autentik diwujudkan dalam bentuk kesantunan, keberadaban, dan kewelasasihan.
SELENGKAPNYA