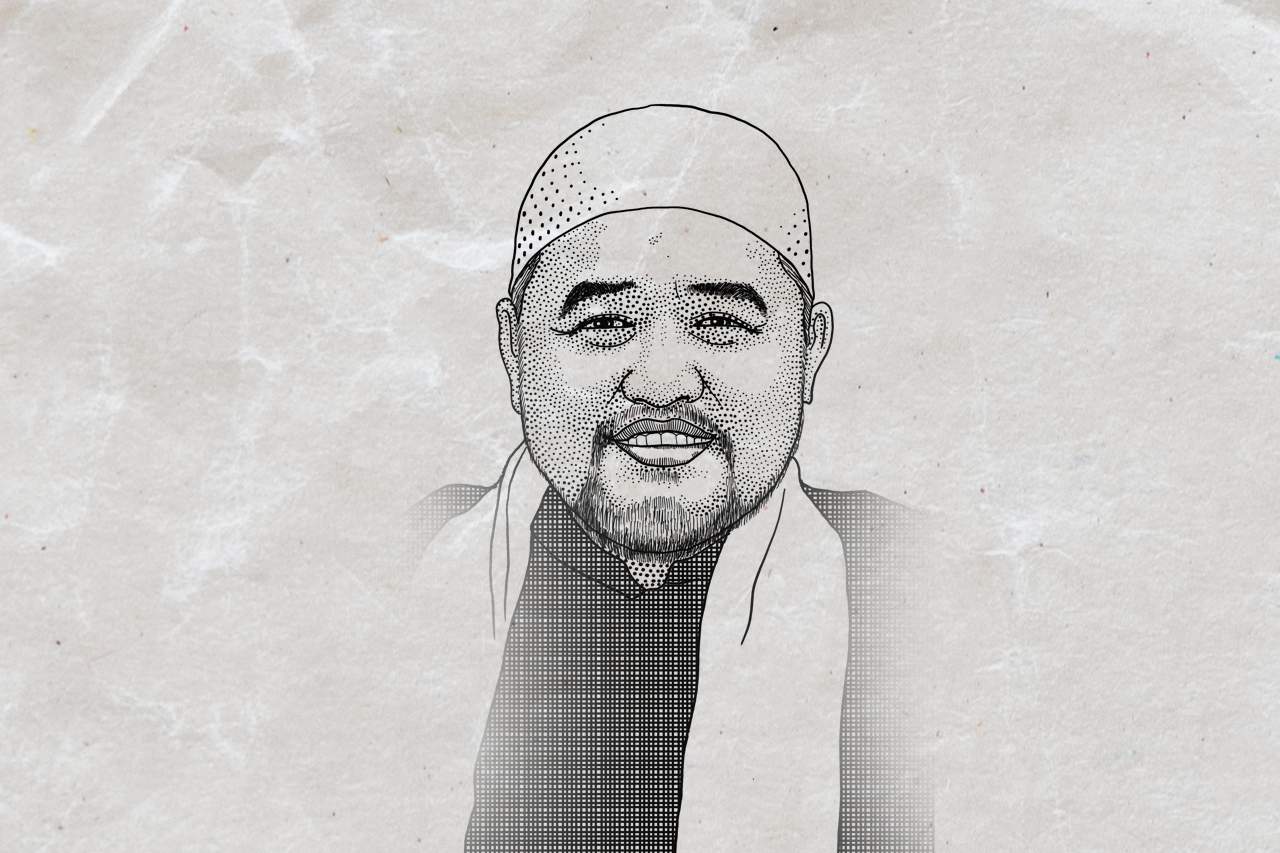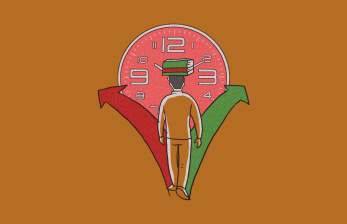Tema Utama
Ibnu Hajar Sang Ulama Pengembara, Penulis Prolifik
Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki kecintaan yang tinggi pada ilmu-ilmu agama.
OLEH HASANUL RIZQA Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki nama lengkap Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Ahmad al-Kinnani. Nisbah itu menunjukkan kabilah tempatnya berasal, Suku Kinanah. Gelar al-Mishri dan asy-Syafii juga kerap ditambahkan pada dirinya. Sebab, ia diketahui berasal dari Mesir dan bermazhab fikih...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Kembali kepada Fitrah
Semoga kita berusaha bersama-sama menjaga kedua makna fitrah tersebut.
SELENGKAPNYAHarapan Setelah Lebaran
Saat silaturahim Lebaran, keluarga besar berkumpul, duduk berdekatan, makan minum satu meja.
SELENGKAPNYA