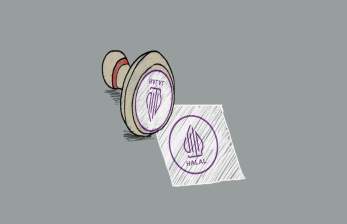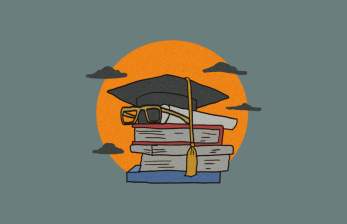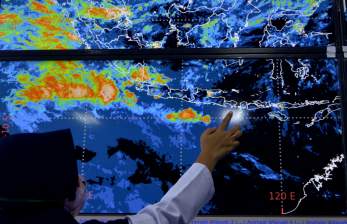Opini
Prahara di Mahkamah Konstitusi
Sistem rekrutmen hakim MK dipertanyakan.
Oleh GALANG ASMARA, Guru Besar Fak Hukum Universitas Mataram
Hari itu, Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 17.40 WIB, sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) selesai mengucapkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkara Judicial Review Pasal 162 q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MK Prof Dr. Anwar Usman, SH, MH Datuak Rajo Alam Batuah, Karaeng Makulle Galesong. Dengan penuh percaya diri semua hakim MK membacakan putusannya setebal 122 halaman secara bergiliran dengan amar putusan antara lain menyatakan:
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
Putusan ini diwarnai Pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) dari para hakim. Selesai dibacakan sejumlah orang berkomentar yang disebabkan karena adanya keanehan dalam putusan tersebut antara lain adanya ketidak konsistenan dengan putusan MK sebelumnya yang mengadili objek perkara yang sama yakni perkara Judicial Review Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Putusan MK sebelumnya yakni Putusan No.29/PUU-XXI/2023, No 51/PUU-XXI/2023 dan No 55/PU-XXI/2023 yang kesemua amar putusannya menyatakan menolak permohonan penggugat karena Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk kategori open legal policy dari pembentuk UU (DPR dan Presiden). MK tidak berwenang mengubah bunyi pasal itu karena Bunyi pasal tersebut adalah kaitannya dengan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini berarti bahwa hanya Pembentuk UU yang berwenang menentukan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan kata lain UUD menghendaki hanya UU yang dapat mengatur Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan siang hari itu justru mengatur syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menambah frase sebagai berikut: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu No 7 Tahun 2017 menjadi berbunyi: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Dengan putusan MK tersebut jelas dan terang Hakim MK telah mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q UU tersebut sekaligus telah mengubah Bunyi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yang kalau dikonstruksikan menjadi berbunyi:
“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Sungguh mengherankan, mengapa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 padahal pada 3 putusan MK sebelumnya dinyatakan sebagai Pasal Open legal policy, artinya MK tidak dapat menambah frase dalam ketentuan tersebut.
Membaca putusan tersebut, sontak para ahli Hukum Tata Negara berkomentar keras termasuk hakim MK sendiri yang memiliki latar belakang ahli Hukum Tata Negara. Bagi ahli Hukum Tata Negara Tidak ada kata yang tepat untuk menyebut Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 tersebut kecuali bahwa Putusan tersebut keliru dan MK telah melampaui kewenangannya atau telah menyalahgunakan kewenangannya mungkin untuk kepentingan tertentu.
Belakangan diketahui bahwa Putusan tersebut patut diduga untuk kepentingan oknum keluarga hakim MK yang hendak menjadi calon wakil presiden dari pasangan calon Presiden tertentu yang notabene ada hubungan keluarga dengan Ketua MK, Anwar Usman.
Betapa tidak, karena Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain keponakan Ketua MK tersebut langsung memanfaatkan putusan MK tersebut untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka jelas tidak memenuhi syarat jika dilihat dari ketentuan Pasal 162 huruf q UU Pemilu tersebut sebelum diubah dengan Putusan MK karena Gibran Rakabuming Raka belum berumur 40 tahun sebagaimana ditentukan sebagai syarat umur minimal untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden.
Kecurigaan bahwa Ketua MK ada kepentingan dalam putusan MK ini yang tidak lain guna meloloskan keponakannya itu setelah diketahui bahwa dalam tiga putusan MK sebelumnya hakim MK semua menolak gugatan yang sama dan Ketua MK tidak ikut bersidang dalam ketiga perkara tersebut. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 Anwar datang ikut dalam persidangan, dan yang mengherankan konon sebelum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) semua hakim juga menolak namun setelah kehadiran Ketua MK tersebut amar putusan menjadi berubah dan bertentangan dengan 3 putusan MK sebelumnya.
Masyarakat pun menaruh curiga atas proses pengambilan putusan MK tersebut sehingga sejumlah kalangan menyampaikan permohonan kepada MK agar Hakim MK yang ada kaitannya dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diadili di Majelis Kehormatan MK dengan tuduhan telah melanggar etika sebagai hakim MK, baik berupa ikut bersidang dalam perkara yang secara langsung dan tidak langsung ada kepentingannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Dan ini juga merupakan pelanggaran hukum yang nyata terhadap Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (5) tersebut, maka menurut Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Pasal 17 ayat (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.
Atas laporan dugaan pelanggaran tersebut MK pun segera membentuk sekaligus melantik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang terdiri atas Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R Saragih. Wahiduddin Adams mewakili unsur hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie mewakili unsur tokoh masyarakat. Kemudian Bintan R. Saragih mewakili unsur akademisi.
Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK diberi waktu bersidang selama 30 hari sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023. Nampaknya MKMK tidak perlu menunggu 30 hari untuk menyelesaikan tugasnya karena pada tanggal 7 November 2023, MKMK sudah menyelesaikan tugasnya dengan menetapkan keputusan sebagai berikut:
1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
Demikian Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung MK pada Selasa (7/11/2023) yang dibacakan oleh Ketua MKMK Prof. Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih.
Dengan diputus bersalahnya Anwar Usman, cukup banyak Ketua Hakim MK yang pernah diberikan sanksi baik dengan tuduhan pelanggaran hukum maupun Etik. Sebelumnya pada tahun 2014, Akil Mochtar dinyatakan bersalah karena menerima suap dalam pengambilan keputusan sengketa pemilihan kepala daerah.
MKMK menilai Akil Mochtar melanggar kode etik dan perilaku hakim yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006. Akil Mochtar juga telah dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 30/06/2014.
Tidak lama berselang pada tahun 2017 Hakim MK Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017). karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap dalam perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain Akil Mochtar dan Patrialis Akbar Mantan Hakim MK, Arif Hidayat juga pernah melanggar etik dan diberikan sanksi etik. Bahkan Arif Hidayat pernah dua kali dituduh melanggar Kode Etik selama menjabat sebagai Ketua MK. Pada 2016, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK dan Pada 11 Januari 2018. Namun pelanggaran etik yang dilakukan tidak berat sehingga hanya diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
Hakim MK berikutnya yang pernah dituduh dan terbukti melanggar etika hakim MK adalah Guntur Hamzah yang sebelum menjadi hakim MK adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2015-2022. Pada 23 November 2022, ia dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggantikan Aswanto untuk periode 2022–2035. Beliau dituduh telah melakukan pelanggaran etik ringan terkait dengan pengubahan substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XX/2022.
Jika melihat banyaknya hakim MK yang telah dinyatakan bersalah melanggar etik maupun disertai dengan perbuatan pidana, maka ini dapat disebut sebagai suatu prahara di tubuh MK. Hal ini pula menjadikan kita patut mempertanyakan sistem rekrutmen hakim MK terutama kaitannya dengan integritas moral.
Padahal mereka telah diberikan predikat sebagai negarawan yang mumpuni dan dipanggil Yang Mulia. Namun dengan banyaknya kasus pelanggaran Etik maupun pelanggaran hakim dari hakim MK bahkan Ketua MK, maka kiranya perlu meninjau kembali sistem rekrutmen hakim MK yang lebih ketat dan lebih memperhatikan kredibilitas moral dari para kandidat calon hakim MK. Jika tidak maka Prahara MK akan terus terjadi.
Kembali pada kasus putusan MKMK yang diucapkan Selasa 7 November 2023, setelah adanya putusan MKMK yang menyatakan Ketua MK dan sejumlah hakim bersalah melanggar etika hakim MK, maka pertanyaannya adalah bagaimana implikasi putusan MKMK tersebut terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Apakah putusan tersebut bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Jika dapat, maka persoalanya adalah siapakah yang membatalkannya atau menyatakan tidak sah. Dapatkah putusan tersebut secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum sehingga terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden kembali kepada ketentuan Pasal 167 huruf q UU Pemilu.
Untuk menjawab persoalan ini ada baiknya kita kembali kepada ketentuan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni ketentuan Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) seperti yang telah diungkapkan di muka. Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut, maka Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 seharusnya dinyatakan tidak sah oleh MK sendiri dan memberikan sanksi administratif kepada Hakim yang dinyatakan memiliki conflict of interest, dan MK bersidang kembali untuk memeriksa permohonan pengujian undang-undang Pemilu Pasal 169 huruf q.
Apabila hal yang demikian tidak dapat dilakukan, maka menurut pendapat penulis, masyarakat hendaknya mengajukan permohonan pengujian kembali terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 karena Pasal tersebut sudah berubah bunyi dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah menambah frase: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu No 7 Tahun 2017 menjadi berbunyi: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Permohonan untuk menguji Kembali Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidaklah dapat dikategorikan nebis in idem karena memang Pasal yang digugat tidak sama bunyinya dengan bunyi pasal sebelumnya meskipun Pasalnya sama.
Hanya dengan cara demikian maka perasaan keadilan dan kepastian hukum Masyarakat dapat dijaga dan pelanggaran hukum dapat ditegakkan dan dihindari.
Pada tahap berikutnya, jika apa yang menjadi harapan pemohon untuk mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu dapat disampaikan kepada Pembentuk UU sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.