
Tema Utama
Ilmu Jiwa Dalam Sejarah Islam
Peradaban Islam-lah yang pertama memiliki rumah sakit, termasuk rumah sakit jiwa.
OLEH HASANUL RIZQA
Pada masa kini, disiplin yang mengkaji aspek jiwa manusia disebut sebagai psikologi. Menurut Prof Ulfiah dalam buku Psikologi Konseling: Teori dan Implementasi (2020), kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni gabungan antara psyche yang berarti ‘jiwa’ dan logos, 'ilmu'.
Maka, secara harfiah psikologi adalah ilmu jiwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan psikologi sebagai ‘ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku'. Pengertian lainnya, psikologi merupakan ‘ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa'.
Akan tetapi, Ulfiah mengatakan, gambaran yang presisi tentang jiwa tidak dapat dipastikan. Sebab, tidak ada seorang pun mengetahui secara detail tentang apa sejatinya jiwa itu. Maka dari itu, psikologi tidak mempersoalkan tentang apa itu jiwa. Disiplin ini mempelajari gejala-gejala atau fenomena kejiwaan.
Dalam sejarah keilmuan Barat, psikologi sesungguhnya dapat dilacak sejak zaman para filsuf Yunani Kuno, semisal Plato atau Aristoteles. Kedua guru-murid itu memandang, manusia merupakan kombinasi antara raga dan jiwa. Yang terakhir itu lebih mulia daripada yang terdahulu.
Sebab, jiwa lebih bersifat abadi dan transenden, sedangkan jasad selalu temporal dan profan. Khususnya bagi Aristoteles, jiwa manusia lebih mulia dibandingkan tanaman dan hewan karena esensinya adalah penalaran.
Setidaknya hingga abad ke-20, psikologi dalam tradisi keilmuan Barat masih dikaitkan dengan filsafat. Barulah sesudah itu, disiplin tersebut cenderung independen dengan menerapkan metode-metode yang ilmiah-empiris. Dengan demikian, psikologi diharapkan dapat memenuhi syarat sebagai sebuah sains modern.
Setidaknya hingga abad ke-20, psikologi dalam tradisi keilmuan Barat masih dikaitkan dengan filsafat.
Pelbagai aliran psikologi (Barat) pun bermunculan. Misalnya, aliran behaviorisme, psikoanalisis, kognitif, humanis, dan neurobiologis. Guru besar psikologi Islam Prof Abdul Mujib mengatakan, dalam perkembangannya kemudian disiplin tersebut menjadi sasaran banyak kritik.
Sebagai contoh, untuk aliran yang meletakkan basis pada kerja-kerja biologis di otak. Psikologi pun dianggap tidak lagi berbasis pada jiwa, melainkan otak. Bahkan, menurut akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu, pandangan materialistis-positivistik seperti itu menjadi arus utama dalam psikologi.
“Sekarang itu, kalau kita baca produk-produk psikologi, sulit ditemukan kata-kata atau terminologi psiko (psyche). Karena, sekarang psikologi tidak belajar lagi mengenai mind, psyche, tapi lebih mempelajari perilakunya. Jadi, psikologi sekarang bukan lagi ilmu jiwa, melainkan ilmu perilaku,” tutur Abdul Mujib kepada Republika beberapa waktu lalu.
Krisis semacam itu agaknya lebih jarang terdengar dari tradisi keilmuan Islam. Pemahaman Barat melakukan sekularisasi terhadap jiwa agar entitas itu dapat didekati secara “ilmiah". Sementara, Islam memiliki sumber informasi yang tepercaya mengenai jiwa. Dari Alquran dan hadis, begitu banyak keterangan tentang entitas tersebut. Itulah yang menjadi pegangan para psikolog atau ahli jiwa Muslim.
Epistemologi yang dipakai psikologi—menurut Islam—tidak hanya mengandalkan yang empiris, tetapi juga metaempiris. Gangguan jiwa, umpamanya, tidak melulu dikaitkan dengan kondisi saraf atau otak seseorang.
Dalam pandangan Islam, apabila orang itu terlalu mencintai dunia (hubbud-dunya), maka ia bisa dikatakan sedang terganggu jiwanya. Agar menjadi normal lagi, jiwa manusia pun mesti kembali ke kondisi tenang dan tenteram, yang dapat ditempuh melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.
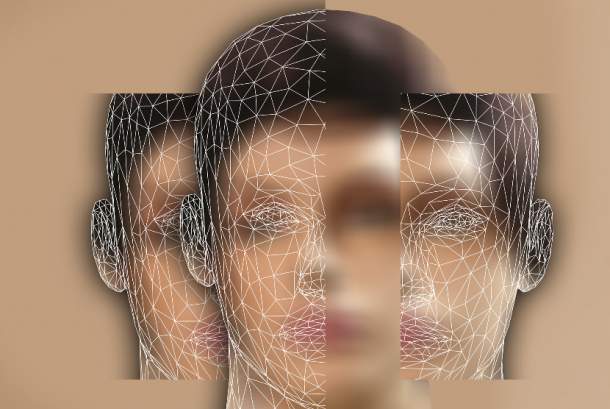
Jejak sejarah
Dr Syamsuddin Arif dalam artikelnya, “Psikologi Dalam Islam” (2009) menjelaskan corak-corak pendekatan yang muncul di sejarah Islam dalam memahami jiwa manusia.
Pertama, pendekatan Alquran-Sunnah. Menurut cara ini, keterangan tentang jiwa manusia merujuk pada dalil-dalil dari sumber ajaran Islam. Salah seorang sarjana yang menggunakan metode ini ialah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (wafat 1350 M).
Dalam kitabnya, Ar-Ruh, murid Ibnu Taimiyyah itu menerangkan tentang nasib jiwa ketika seseorang telah meninggal. Berdasarkan pembacaannya atas ayat-ayat kitab suci dan hadis Nabi SAW, jiwa atau ruh seorang yang wafat dapat merasakan siksa atau nikmat kubur sekalipun jasadnya sudah hancur.
Kedua, pendekatan filsafat. Arif mengatakan, ancangan tersebut muncul seiring dengan maraknya penerjemahan naskah-naskah Yunani Kuno ke bahasa Arab. Peradaban Islam sejak abad ke-10 sangat gencar mengumpulkan dan menelaah pelbagai teks ilmu pengetahuan dari luar Arab. Tidak hanya Yunani, tetapi juga India, Cina, dan lain-lain.
Mulai masa itu, para sarjana Muslim yang menaruh perhatian pada masalah jiwa turut mengomentari pandangan filsafat Yunani Kuno. Mereka bahkan banyak dipengaruhi oleh teori-teori jiwa, semisal dari Plato dan Aristoteles.
Menurut Arif, hal itu tidak mengherankan. Sebab, Aristoteles memang seorang filsuf yang kerap mengupas aneka persoalan jiwa manusia dengan sangat logis dan teperinci. Teori-teorinya tertuang dalam karyanya, De Anima dan Parva Naturalia. Adapun gurunya, Plato, menjadi pemikir pertama yang tercatat dalam sejarah mengajukan teori tentang tiga aspek mental manusia: rasional, hewani (persepsi), dan vegetatif (nutrisi).
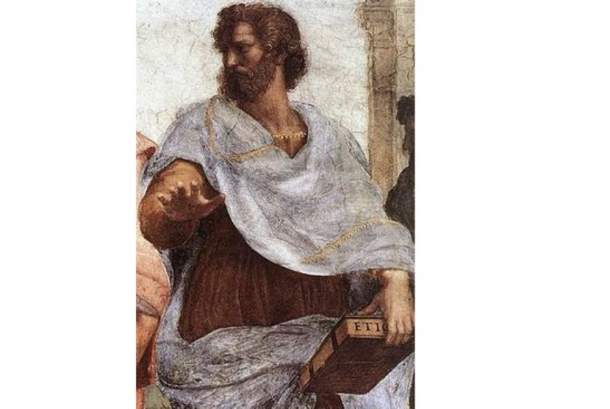
Hingga usainya era keemasan Islam, banyak filsuf Muslim yang terinspirasi dari Aristoteles dalam menelaah persoalan jiwa. Sebut saja, Ibnu Miskawaih, Abu Bakar ar-Razi, Ibnu Rusyd (Averroes), dan Abu Barakat al-Baghdadi. Mereka semua memiliki kesamaan pandangan tentang jiwa, yakni sebagai entitas yang paling signifikan dalam diri manusia. Tanpa jiwa, manusia tak berarti apa-apa.
Ketiga, pendekatan sufistik. Arif memaparkan, kaum sufi menjelaskan tentang jiwa manusia berdasarkan pada pengalaman spiritual. Dibandingkan dengan psikologi para filsuf yang terkesan sangat teoritis, lanjut akademisi Universitas Darussalam Gontor itu, apa yang ditawarkan para sufi lebih praktis dan eksperimental. Beberapa nama salik yang dapat digolongkan sebagai tokoh ancangan ini ialah Al-Hakim at-Tirmidzi (wafat 898 M), Abu Thalib al-Makki (wafat 996 M), dan Imam al-Ghazali (wafat 1111 M).
Dalam karya monumentalnya, Ihya Ulm ad-Din, al-Ghazali menjelaskan bagaimana jiwa manusia dapat dilanda pelbagai gangguan, seperti iri hati, waswas, keserakahan, dan sebagainya. Sebagai contoh, sifat dengki bisa merasuki jiwa siapapun, baik orang fasik maupun saleh.
Pemicu yang memunculkannya, antara lain, ialah fanatisme. Dengan berjiwa fanatik terhadap tokoh, golongan, atau pendapat tertentu, seseorang akan cenderung memandang yang-berbeda dengan sebelah mata alias merendahkan atau bahkan mengejek.

Prof Raghib as-Sirjani dalam buku Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia memaparkan, Islam pun berkontribusi besar dalam memajukan dunia psikologi. Peradaban Islam-lah yang pertama memiliki rumah sakit, termasuk rumah sakit jiwa.
Ratusan tahun sebelum masyarakat Eropa mengenal institusi pelayanan kesehatan mental, Dinasti Abbasiyah telah membuka rumah-rumah sakit yang khusus menangani pasien dengan gangguan kejiwaan. Pada 705 M, di Baghdad diketahui telah berdiri sebuah rumah sakit jiwa. Di sanalah, para dokter dan psikolog Muslim mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya.
Masih pada awal abad kedelapan Masehi, peradaban Islam yang bersemi di Afrika Utara pun tak kalah menakjubkannya. Di Kota Fes, Maroko, sebuah rumah sakit jiwa didirikan. Begitu pula dengan Kota Kairo, Mesir, tepatnya pada 800 M. Setelah itu, pada tahun 1270 M, Kota Damaskus dan Aleppo (Halab), Suriah, juga mulai memiliki rumah sakit jiwa.
Pada 705 M, di Baghdad diketahui telah berdiri sebuah rumah sakit jiwa. Di sanalah, para dokter dan psikolog Muslim mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya.
Sebagai perbandingan, Inggris baru mulai memiliki rumah sakit jiwa pada 1831 M. Namanya adalah Middlesex County Asylum yang berlokasi di Hanwell, sebelah barat London. Pemerintah setempat mendirikannya setelah muncul desakan dari publik, yang mengerucut pada disepakatinya aturan Madhouse Act pada 1828.
Belajar dari sejarah, perkembangan keilmuan psikologi di Barat dan Islam pun hendaknya dijembatani satu sama lain. Dalam hal ini, Syamsuddin Arif menilai, masih banyak khazanah psikologi Islam yang perlu diselami dan disebarluaskan ke masyarakat.
Memang, ia mengakui, ada pelbagai kendala untuk mewujudkan upaya-upaya demikian. Sebut saja, syak wasangka terhadap dunia intelektual Islam di satu sisi yang kerap luput dipandang daripada Barat. Kedua, dan mungkin yang lebih parah, ialah fanatisme terhadap psikologi modern (Barat). Padahal, seperti sudah dijelaskan di atas, dunia keilmuan Barat pun dilanda krisis. Terkait psikologi, terasa bahwa ilmu jiwa ini justru tidak ada (membahas) jiwa.
“Psikolog Muslim tinggal memilih, mau terus-terusan merujuk Freud, Skinner, Maslow, Ellis, dan sebagainya, atau belajar dari para ahli psikologi Islam?” tanyanya retoris.
Psikolog Muslim tinggal memilih, mau terus-terusan merujuk Freud, Skinner, Maslow, Ellis, dan sebagainya, atau belajar dari para ahli psikologi Islam.
Sang Perintis Psikologi Islam
Abu Zaid al-Balkhi (850-934 M) merupakan salah satu tokoh dalam sejarah psikologi. Pemilik nama asli Ahmad bin Sahl itu sesungguhnya adalah seorang pakar multidisiplin ilmu pengetahuan (polymath). Bagaimanapun, jasanya dalam bidang ilmu jiwa begitu signifikan. Dialah yang disebut-sebut sebagai perintis psikologi Islam.
Cendekiawan Persia itu menulis banyak karya, di antaranya adalah Masalih al-Abdan wa al-Anfus. Di dalamnya, ia memperkenalkan istilah terapi kesehatan jiwa (thibb ar-ruhani). Menurutnya, pengobatan yang hanya berfokus pada kondisi fisik tidaklah cukup. Seorang dokter atau ahli medis juga perlu memperhatikan aspek mental atau kejiwaan pasien.
Dalam masa sekarang, topik yang diusung sang cendekiawan Muslim itu kerap disebut sebagai psikosomatis. Ini merupakan kondisi ketika suatu penyakit fisik yang muncul diduga disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental seseorang. Di antara gejala-gejala psikosomatis adalah jantung yang berdebar-debar, sesak napas, dan nyeri pada seluruh tubuh.
Rihlah yang dijalani al-Balkhi hingga menjadi ahli ilmu jiwa bermula sejak dini. Seperti tampak dari namanya, lelaki ini lahir di wilayah Balkh—kini termasuk Afghanistan. Ayahnya merupakan seorang guru. Demi mendukung kesuksesan anaknya, sang bapak pun mengirimkannya ke pelbagai syekh untuk menimba ilmu.

Hingga akhirnya, al-Balkhi merantau ke Baghdad. Selama delapan tahun, dirinya belajar dan bekerja di pusat Negeri Abbasiyah tersebut. Waktu itu, Abbasiyah sedang mengalami kekacauan politik dan sosial. Bahkan, wilayah kekhalifahan ini menyusut hingga menyisakan Baghdad dan sekitarnya.
Bagaimanapun, al-Balkhi tidak begitu terpengaruh oleh kondisi negara yang carut-marut. Dirinya tetap dengan tekun menuntut ilmu, melanjutkan tradisi intelektual Islam.
Melalui Masalih, ia mengkritik dunia kedokteran di masanya yang cenderung memusatkan perhatian pada penyakit fisik pasien. Padahal, menurutnya, banyak orang yang dirawat di rumah sakit pun mengalami gangguan kejiwaan.
Malahan, ia mengajukan hipotesis, penyakit fisik patut diduga mempengaruhi kondisi kognitif dan kejiwaan si pasien. Pun berlaku sebaliknya: keadaan psikis seseorang yang terganggu bia menyebabkannya rentan terserang penyakit (fisik).
Al-Balkhi menjadi yang pertama mendeteksi perbedaan antara neurosis dan psikosis. Ia pun yang pertama kali merintis terapi kognitif dalam rangka mengkaji pengelompokan gangguan penyakit ini. Ilmuwan tersebut mengelompokkan penyakit mental-kejiwaan ke dalam empat bagian, yaitu ketakutan dan fobia (al-faza); agresi dan amarah (al-ghadab); kesedihan dan depresi (al-jaza); serta obsesi (was was al-sadr).
Sebagai contoh, untuk mengatasi al-jaza, seorang tabib dapat menerapkan terapi internal dan eksternal. Internal berarti, si pasien didorong untuk menanamkan pikiran-pikiran positif yang bisa menangkal kesedihannya.
Umpamanya, menguatkan keyakinannya bahwa kematian orang yang dikasihinya adalah takdir Allah SWT yang mengandung hikmah tertentu. Adapun terapi eksternal dapat dilakukan dengan memberikan nasihat atau membuka obrolan persuasif dengannya.
Di antara nasihat al-Balkhi yang terkenal ialah, “Kematian adalah keniscayaan. Janganlah engkau takut padanya. Jika engkau takut pada apa yang akan terjadi setelah kematian, perbaikilah dirimu sebelum kematian menjemputmu. Takutlah akan perbuatan-perbuatan jahat (yang engkau lakukan), bukan pada kematianmu!”
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.







