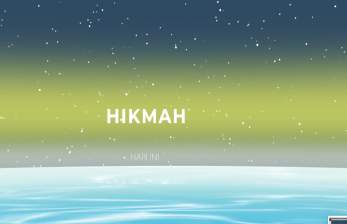Mujadid
KH Noer Muhammad Iskandar, Gigih Berdakwah di Ibu Kota
KH Noer Muhammad Iskandar berhasil mendirikan salah satu pondok pesantren terbesar di Jakarta.
OLEH HASANUL RIZQA
Syiar Islam di Jakarta tidak hanya berlangsung di berbagai masjid atau majelis pengajian, tetapi juga pondok-pondok pesantren. Ya, geliat kehidupan kaum santri pun dapat dijumpai di Ibu Kota.
Salah satu lembaga yang terkemuka di sana ialah Pondok Pesantren Asshiddiqiyah. Lokasinya berada di Jalan Panjang, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Pendirinya merupakan seorang ulama terkemuka, yakni Dr KH Noer Muhammad Iskandar SQ. Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, itu terbilang sukses dalam merintis dan membesarkan Asshiddiqiyah.
Hingga kini, lembaga tersebut sudah memiliki belasan cabang, baik di dalam maupun luar kota Jakarta. Pesantren itu mengusung metode pembelajaran modern yang diselaraskan dengan sistem klasik dan tradisi.
Kiai Noer lahir pada 5 Juli 1955. Sejak awal, putra pasangan Kiai Iskandar dan Nyai Rabiatun itu tumbuh besar di lingkungan santri. Pendidikan agama diperolehnya pertama-tama melalui kedua orang tuanya. Selanjutnya, ia menuntut ilmu di sejumlah pondok pesantren tradisional di Jawa Timur.
Noer kecil mulai menerima pendidikan formal di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, pemuda ini meneruskan rihlah keilmuannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Lembaga tersebut kala itu diasuh KH Makhrus Aly. Selama menjadi santri, ia pernah memimpin Ikatan Santri Banyuwangi. Dirinya terus belajar dengan penuh disiplin dan ketekunan hingga akhirnya lulus pada 1974.
Selama menjadi santri, ia pernah memimpin Ikatan Santri Banyuwangi.
Noer muda bercita-cita untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Karena itu, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Tujuannya adalah menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta. Selama tinggal di Ibu Kota, ia mulai mengamati dan bahkan mengalami sendiri perbenturan antara budaya tradisional dan metropolitan.
Akan tetapi, dirinya tidak larut pada kehidupan perkotaan. Bahkan, lelaki ini sedikit demi sedikit memahami bahwa antara dua bentuk kebudayaan itu sesungguhnya dapat diselaraskan. Perpaduan keduanya dapat menjadi jalan untuk syiar Islam melalui dakwah dan pendidikan.
Mulai saat itu, terbayang dalam benaknya untuk mendirikan pondok pesantren di kawasan perkotaan. Lembaga yang tetap berakar pada budaya tradisional, tetapi pada saat yang sama mampu menyatu dengan kehidupan masyarakat urban.
Pada 1980-an, Jakarta kian bergeliat sebagai wajah Indonesia modern. Gedung-gedung pencakar langit mulai banyak berdiri. Kelas menengah semakin banyak bermunculan. Kebanyakan mereka adalah kaum Muslimin yang berpendidikan tinggi dengan akar budaya dari daerah-daerah.
Secara keseluruhan, Indonesia kala itu mengalami peningkatan taraf ekonomi yang cukup baik. Dan, Jakarta adalah wilayah yang paling merasakan dampak manis dari orde pembangunan itu.
View this post on Instagram
Mengamati dua dunia
Kiai Noer saat itu termasuk generasi muda santri yang mengalami migrasi kultural, yakni dari daerah ke perkotaan. Ia adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan lulusan pondok-pondok pesantren yang berhasil menyeberang sekat-sekat kultur dan geografis untuk menuju kawasan urban.
Tidak ada perasaan kagetan saat menghadapi budaya baru. Justru, ia dengan cermat mengamati adanya peluang untuk menumbuhkan kebudayaan tradisional santri di tengah Ibu Kota.
Baginya, efektivitas syiar Islam, antara lain, bersandar pada kemampuan seorang dai dalam “membaca” peta sosiologis daerah tempatnya berada. Bila seorang ahli agama tidak mampu memahami situasi simbolik masyarakat kota, akan tipis kemungkinan baginya untuk diterima dalam kelompok sosial yang dihadapinya.
Seperti dilansir dari situs resmi Pesantren Asshiddiqiyah, suami Nyai Siti Nur Jazilah itu pernah mengibaratkan posisi seorang mubaligh seperti sopir yang harus menjalankan mobil dengan lima gigi.
Sang sopir hanya bisa menghitung secara pas kapan harus berjalan dengan gigi satu, dua, tiga, empat, hingga lima. Dirinya harus terampil untuk berpindah persneling secara cepat dan tepat, tanpa membuat mobil yang dikendarainya terhentak-hentak.
Dengan begitu, penumpangnya—yakni jamaah dan para santri—pun tidak mengalami gegar budaya. Alih-alih kaget, mereka justru akan menerima secara terbuka atau bahkan menyukai kebudayaan tradisional yang dibawa pesantren.
Begitu lulus dari PTIQ, Kiai Noer semakin dikenal sebagai seorang dai di tengah masyarakat. Ia pun terus berupaya untuk mewujudkan impiannya, membangun sebuah pondok pesantren di Jakarta. Dan, hal itu dilakukannya dengan penuh perjuangan. Berbagai tantangan dihadapinya untuk merealisasikan cita-citanya itu.
Selama merantau di Jakarta, Kiai Noer masih merawat silaturahim dan komunikasinya dengan para gurunya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Secara rutin, dirinya meminta nasihat kepada KH Makhrus Aly. Sang pengasuh Pesantren Lirboyo itu pun kerap menyemangatinya agar pantang menyerah dalam mewujudkan asanya.
Salah satu petuahnya adalah, keberadaan pondok pesantren begitu penting dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Islam yang berwawasan luas sekaligus berakhlak mulia.
Keberadaan pondok pesantren begitu penting dalam mewujudkan SDM Islam yang berwawasan luas sekaligus berakhlak mulia.
Sambil terus berusaha, Kiai Noer juga merumuskan keadaan yang diamatinya. Dalam pandangannya, ada perbedaan yang cukup mencolok dari dunia santri dan dunia akademik. Umumnya pondok-pondok pesantren—terutama di pelbagai daerah—menerapkan metode pengajaran dengan pendekatan dogmatis.
Artinya, para santri harus menuruti, “sami’na wa ata’na”, kepada sosok kiai atau ulama setempat. Akibatnya, pemahaman akan Alquran sebagai jalan hidup (way of life) pun sering kali terbatas, yakni berkutat pada aspek-aspek ibadah saja.
Sementara itu, kalangan akademisi kampus-kampus, apalagi yang berbasis sekuler, cenderung memahami Alquran dengan pendekatan rasionalistik. Mereka menempatkan Alquran sebagai sebuah objek kajian akal.
Alhasil, ayat-ayat yang tak mampu disentuh akal pikiran mereka, dengan mudah dipangkas. Bahkan, menurut Kiai Noer, tampak ada kecenderungan dari mereka untuk “memenangkan” budaya lokal tatkala bersinggungan dengan ketentuan Alquran.
Pengamatan atas kedua dunia itu—santri dan akademik sekuler—membuatnya semakin bersemangat dalam merumuskan, pesantren macam apa yang kelak akan didirikannya di Ibu Kota. Berdasarkan pemahaman dan pengalamannya selama menempuh studi di PTIQ, ia pun mengambil kesimpulan bahwa seorang santri haruslah mampu membuka wawasan yang seluas-luasnya untuk memahami Alquran dan Sunnah Nabi SAW lebih dari sekadar aspek-aspek ubudiah.
Apalagi, pada faktanya begitu banyak ajaran Kitabullah yang hingga kini belum tergali, dan tak akan pernah selesai tergali sampai kiamat. Singkatnya, santri tak boleh hanya sibuk mendaras kitab, tetapi lebih lanjut menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari.
View this post on Instagram
Mendirikan pesantren
Bersama dengan beberapa kawannya, Kiai Noer mendirikan Yayasan al-Muchlisin di Pluit, Jakarta Utara. Nama yayasan itu sesuai dengan nama Masjid al-Muchlisin di daerah yang sama. Pelbagai aktivitas keagamaan yang dirintisnya lambat laun mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Dirinya pun semakin dikenal sebagai seorang dai yang berilmu luas lagi piawai dalam berdakwah.
Waktu itu, Kiai Noer sudah menikah dengan Siti Nur Jazilah, putri KH Mashudi asal Tumpang, Malang, Jawa Timur. Istrinya itu punya pengalaman memimpin sebuah pondok pesantren putri di Tebuireng, Jombang. Walaupun hidup serba berkecukupan, pasangan suami-istri ini selalu bersemangat dalam berdakwah.
Suatu hari, Kiai Noer kedatangan tamu, Ir H Bambang Sudayanto. Sahabatnya itu bekerja sebagai kepala PPL Pluit. Kepada sang kiai, Bambang menuturkan bahwa dirinya sukses dengan pekerjaannya terkait Pantai Mutiara Indah Kapuk. Sebagai ungkapan terima kasih, Kiai Noer pun diberi sebuah kios kecil di Pluit dan diberangkatkan ke Tanah Suci.
Dalam proses menyelesaikan berkas pendaftaran haji, ia berjumpa dengan kawan lama, yakni H Rosyidi Ambari, yang saat itu menjabat asisten menteri agama. Ternyata, H Rosyidi sudah lama ingin bertemu dengan dirinya. Sebab, ada amanah di tangannya untuk mengelola sebidang tanah di bilangan Kedoya agar dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam.
Ada amanah di tangannya untuk mengelola sebidang tanah di bilangan Kedoya agar dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam.
Kiai Noer tak langsung mengiyakan. Malam harinya, ia melaksanakan shalat istikharah. Hatinya mendapatkan isyarat, lahan itu baik dan prospektif sebagai lokasi pesantren.
Seusai ibadah haji, dirinya kembali memikirkan kemungkinan mendirikan pesantren di lahan di Kedoya itu. Setelah mendengarkan berbagai pertimbangan dari sejumlah gurunya, Kiai Noer lantas kembali menemui H Rosyidi.
Keduanya lantas bertamu ke rumah H Djaani selaku pemilik lahan tersebut. Akhirnya, tanah seluas 2.000 meter persegi diamanahkan kepada Kiai Noer. Setelah disepakati, langkah pertama yang dilakukannya adalah membangun sebuah musala kecil di sana.
Dari waktu ke waktu, di sekitar musala itu mulai dibangun asrama dan bangunan kelas. Kini, lahan wakaf itu telah berkembang menjadi seluas 2,4 hektare—seluas Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

Abah Noer Dalam Kenangan
Kabar duka datang dari pihak keluarga Dr KH Noer Muhammad Iskandar SQ sekitar pertengahan Desember 2020. Pada Ahad, 13 Desember 2020, sang pendiri Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta itu berpulang ke rahmatullah. Mubaligh kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, itu meninggal dunia pada usia 65 tahun.
Selama hidupnya, sosok yang akrab disapa Abah Noer itu berkhidmat dalam dunia dakwah dan pendidikan. Ia merupakan salah seorang kiai yang sukses mendirikan pesantren di Ibu Kota. Lembaga yang didirikannya memadukan antara tradisi kaum sarungan dan wawasan masyarakat perkotaan yang dinamis.
Melansir dari situs resmi Asshiddiqiyah, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Syamsul Ma’arif mengatakan, sosok Abah Noer adalah pribadi yang berilmu, saleh, dan sekaligus penggerak dakwah Ahlus sunnah wa al-jamaah (aswaja).
Kiai Syamsul menuturkan kisah ketika Abah Noer baru mengawali dakwahnya di Jakarta pada 1991. Waktu itu, suami Hj Siti Nur Jazilah ini merasa terheran-heran. Ternyata, di Ibu Kota pun masih ada majelis-majelis pengajian khas seperti di kampung-kampung. Hal itu pun kian menambah semangatnya untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di Jakarta.
Ahad, 13 Desember 2020 M / 28 Rabiul akhir 1442 H Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummahjurni fi mushibati... Dikirim oleh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta pada Minggu, 13 Desember 2020
Dahulu, sebelum maraknya televisi syiar Islam dilakukan pula melalui siaran radio. Kiai Noer mendapatkan kesempatan untuk mengisi pengajian yang disiarkan stasiun radio CBB. Menurut Kiai Syamsul, pengajian yang dibawakan sang alim masih kental akan guyonan khas pengajian kampung. Di samping itu, tutur katanya dalam berdakwah pun selalu halus, tidak pernah berkata kasar apalagi sampai mencaci-maki siapa pun.
“Maka seyogianya para mubaligh mencontoh apa yang dilakukan Kiai Noer,” ujar Kiai Syamsul.
Kisah lainnya adalah, suatu kali Abah Noer pernah melakukan dakwah. Untuk sampai tujuan, dirinya menumpangi mobil yang dikemudikan sopir. Waktu sudah tengah malam, ia lantas meminta sang sopir untuk berhenti sejenak. Sebab, dirinya hendak melaksanakan shalat malam, padahal kondisi tubuhnya sendiri tampak begitu lelah.
View this post on Instagram
“Masya Allah, beliau kalau dakwah ke luar kota, sesibuk apa pun, secapek apa pun, di perjalanan tengah malam beliau minta berhenti. Ya itu tetap melaksanakan shalat malam,” kenangnya.
Yang sulit ditiru dari Abah Noer ialah keikhlasannya. Menurut Kiai Syamsul, perkembangan Pesantren Asshiddiqiyah adalah karunia Allah SWT. Sebab, upaya-upaya Abah Noer untuk merintis dan membesarkannya semata-mata demi mencari ridha Ilahi.
“Kepergian Kiai Noer Muhammad Iskandar begitu dalam dirasakan masyarakat, khususnya Jakarta, warga Nahdliyyin dan keluarga besar Asshiddiqiyah tentunya. Semoga dari Asshiddiqiyah, lahir generasi Kiai Noer selanjutnya di mana-mana,” katanya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.